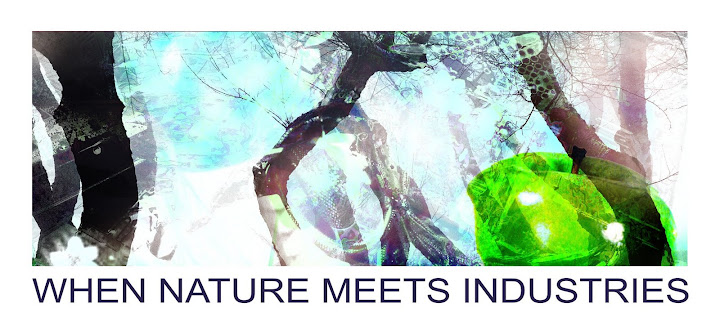Agnes Monica ulang tahun, tapi bukan itu yang mau gue tulis.
Quickview: nggak perlu, yang jelas ini bakalan panjang.
Sekedar kata pengantar yang sama sekali nggak ringkas.
Jam 6 sore gue memutuskan untuk ke studio (baca: lapak) Roni, temen residensi gue dari ISI. Seperti yang sering kita dengar dari para bhiksu, “Isi adalah kosong, kosong adalah isi”. Tapi Roni tidak beragama Buddha. Itu Trisno yang beragama Buddha, dan herannya dia juga dari ISI, tapi dia juga peserta residensi.
Sebelum cerita berlanjut, mungkin ada yang, walaupun ingin bertanya, tapi merasa hidupnya akan menjadi sia-sia jika harus sampai mengacungkan jari. Kenapa studio dalam tulisan ini harus dibaca lapak? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah karena memang lebih mirip lapak ketimbang studio.
Nah, tidak seperti yang kalian kira, gue ke studio Roni bukan untuk bicara dengan Roni. Gue ke sana justru karena tidak ada kepentingan apa-apa dengan Roni. Mungkin kalian yang membaca keheranan dengan tingkah laku gue, tapi gue pribadi udah nggak heran lagi dengan kalian yang begitu mudahnya keheranan.
Sampai di sana ternyata ada Ucok, itu temen dari ISI juga. Jadi kami bertiga di studio yang mirip lapak itu. Iqi a.k.a Chipow, Patriot a.k.a Mukmin a.k.a Majong, Luthfi a.k.a Bala, dan Walid sudah terlebih dahulu berpulang mendahului kami. Dua yang disebut pertama temen seangkatan gue dari ITB, dua sisanya dari IKJ. Jangan tanya gue mereka semua dari studio mana, tanya aja mereka kenapa milih studio itu. Karena dengan cara itu, kalian juga akan mendengarkan curhat mereka tentang dunia seni yang mereka geluti selama ini. Apa gunanya kalian bertanya mereka dari studio mana kalau kalian tidak tahu apa yang mereka kerjakan di studio? Atau jangan-jangan mereka memang tidak pernah bekerja di studio?
Nggak lebih dari semenit gue sampai sana, Ucok menerima telefon.
“Halo!” katanya. Tapi kata-kata selanjutnya gak gue pedulikan, karena buat apa mengurusi urusan orang lain? Mereka toh sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan masa depan mereka sendiri. Buktinya, toh mereka bisa jadi sarjana. Dan dari telefon itulah cerita berkembang, walaupun sama sekali nggak wangi.
“Eh!” Tegur Ucok, “Kau jadi balik sekarang?”
“Tar lagi. Napa? Lo mo cabut sekarang juga emangnya?”
“Iya. Aku harus ke Slipi. Males macetnya kalau kemalaman.” Ya, dari namanya kalian pasti tahu gimana cara dia ngomong kata males dan macet. Tapi kalau kalian ekspatriat, mungkin kalian tidak bisa mengimajinasikan apalagi menangkap apa yang saya maksud di sini.
Selanjutnya, gue akan melanjutkan kelanjutan cerita berlanjut ini sampai situ.
Pembicaraan berlanjut pada kesepakatan kami berangkat bareng setelah Ucok terlebih dahulu kencing di toilet umum yang disediakan gratis di sana. Dan walaupun dialog antara gue dan Ucok terjadi di studio Roni, tapi satu-satunya pembicaraan dengan Roni yang gue inget adalah saat gue mau cabut dan kami saling mengingatkan untuk berhati-hati. Entah apa maksudnya, mungkin sudah tradisi orang Jawa untuk mengatakan hal itu. Itu si Roni kalau tidak salah, berarti benar, dari Jepara.
Kami berjalan kaki hingga shelter bus Gondola dan menunggu bis gratisan yang melewati jalur arah barat. Bis pergi di saat kami masih sekitar 20 meter dari shelter. Tapi bis itu bukanlah satu-satunya di Ancol, seperti juga tidak cuma satu perempuan di dunia ini (Hey!). Maka kami tetap berjalan dengan langkah yakin. Jelas keyakinan kami tidak bertepuk sebelah tangan, karena setelah berdiri lama akhirnya bis yang lain datang. Kami masuk berebutan dan saling berdesakan. Tapi untung kami kebetulan pria lajang yang belum terikat perempuan manapun, jadi kalau bersenggolan tidak ada yang melarang (Hey!!). Kalaupun itu bukan muhrimnya tapi toh nggak ada yang protes. Karena bagaimana pun juga, sekedar bersenggolan di bis gratisan yang penuh sesak itu tidaklah bijaksana kalau sampai harus dibilang haram. Memang tak kenal maka tak sayang, tapi bukan berarti harus bermusuhan saat di naik bis berbarengan. Apalagi jika harus sampai pukul-pukulan. Sayangnya pertemanan pun sering pula dijadikan alasan untuk melambaikan tangan karena takut terdampar di tengah jalan (Hey!!!).
Tantangan selanjutnya, sekumpulan bau amburadul yang entah apa saja.
Asal tau saja, saat ini masih musim liburan anak sekolah. Herannya kenapa gue dan Ucok yang udah sarjana malah kena imbasnya. Buktinya, turun dari bis gratisan wara-wiri itu kami harus bersiap pula menghadapi antrian di bridge busway shelter. Waw! Itu istilah baru.
Gue kasih Rp 5.500,- ke mbak-mbak penjual karcis. Maksudnya biar dikasih kembalian Rp 2.000,- karena nanti gue naik bis Metro Mini nomer 62 dengan tarif segitu. Biar praktis. Uang kembalian dan karcis gue masukin kantong, dan karcis gue kasih ke petugas setelah gue kencing. Mungkin petugas itu tadinya pemarah, tapi kemudian dengan merobek-robek karcis dia menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Mungkin bagi anda yang pemarah, menjadi petugas penyobek karcis busway bisa menjadi pilihan terapi yang menarik.
Gue dan Ucok ngobrol sembari menunggu busway yang entah di mana supirnya. Heran, kenapa sebutannya busway padahal di badan bis jelas-jelas tulisannya Transjakarta? Tapi bukan itu yang kami obrolkan. Kami mengobrolkan bagaimana caranya berpameran di Galeri Soemardja. Agak geli juga sebenernya, direktur Galeri Soemardja namanya juga Ucok, dan gue biasa panggil dia Bang Ucok. Nah, kalau kata Bang dihilangkan, dalam konteks pembicaraan ini, yang akan merespon langsung adalah si Ucok temen gue yang dari ISI ini. Agak merepotkan emang. Tapi nggak apa-apa, karena ada busway lewat yang kontan disoraki “Huuu!!!” karena dia langsung cabut tanpa mengangkut satu penumpang pun. Hahaha, sialan.
Nah, nggak berapa lama setelah si pseudo-bus itu lewat, akhirnya datang bis gandeng yang mengangkut hampir setengah shelter. Dalam hati gue cuma bisa bilang “Sialan! Kenapa cuma bawa setengah shelter?” Akibatnya gue harus mengantri di samping cowok sok jangkung tapi gendut dengan bau keringatnya yang aduhai. Tapi biarin, pasang MP3 Homicide yang bising-bising juga sudah cukup membalaskan dendam gue. Nyahaha. Dan si cowok nampak kesal, mungkin karena dia keki tapi gengsi kalau harus sampai memamerkan kekuatannya di depan pacarnya. Tapi kalau dia mau ngajak bertengkar, ya nggak apa-apa. Bukankah bumbu pertengkaran yang baik akan mempererat ikatan pertemanan? Toh gue juga punya otak buat ngelawan ototnya dia, dan nggak mahir karate juga nggak berarti gue nggak bisa kung-fu. Nah, itu dia sudah kalah poin dari gue, karena itulah kami tidak sampai berkelahi. Walaupun dia sempat mendengus beberapa kali saat gue ganti track ke lagu Padi. Mungkin, karena yang di depannya itu bukan pacarnya, melainkan dia masih Menunggu Sebuah Jawaban (Hey!!!!). Tapi kalaupun benar gue nggak mau tau urusan orang lain, karena orang lain juga nggak pernah ngurusin gue. Toh gue juga memang dari dulu kurus, nggak seperti dia itu, gendut.
Setelah sengit bertengkar dalam pikiran kami masing-masing, dengan saling menghina dan melemparkan strategi, kami pun berbaikan. Kami saling meminta maaf dalam pikiran kami sendiri. Kebetulan bis datang, dan si Ucok dengan lekas mendorong gue masuk.
Dan hari belum berakhir. Masih ada kemungkinan nggak penting yang bisa saja akan terjadi. Sebut saja, seperti ban busway yang pecah mendadak di daerah Senen misalnya.
Bukan cuma gue kok yang nggak suka orang yang bertele-tele. Banyak juga orang yang ngaku begitu tapi omongannya muter-muter kayak keong (Hey!!!!!). Masalahnya, rumah keong itu mengikuti azas golden section (atau apalah itu namanya), makanya dia bisa oke. Mungkin orang yang bertele-tele tapi kalo mukanya kaya rumah keong bisa mendatangkan hoki juga. Nah, kalo gue bukan bertele-tele, tapi jelas-jelas ngelantur dan ngawur. Karena kalo nggak gitu cerita ini akan beres hanya dalam 1 paragraf. Coba liat, sejauh ini kalian sudah baca berapa? Karena kalau dibaca sampai sejauh ini, ceritanya memang nggak penting, tapi yang penting adalah memaknai sesuatu yang nggak penting hingga menjadi (seolah-olah) penting. Kalo boleh meminjam istilah yang pernah dilontarkan temen SMA gue dalam judul film pendeknya, Ignaz a.k.a Didz bersama Radian a.k.a Jawa, maka tulisan ini menjadi suatu Cela Cendekia yang menyenangkan. Setidaknya buat gue.
Ya, jadi ada satu dialog lucu yang terjadi di shelter Mangga Dua. Itu bis yang sama yang sedang gue naikin yang jadi saksi bisu dialog aneh ini. Bis yang sama yang harus berdesakan satu jam hingga akhirnya mau dinaiki. Dasar kuda!
Shelter itu penuh sesak dan sedari sejam yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan. Signifikan sih yang datang, tapi yang terangkut dikit. Dan bis berhenti di shelter itu, seperti biasa membuka pintu. Entah formalitas entah apa, pintu langsung ditutup kembali. Ya, jelas-jelas bisnya sudah penuh memang. Mungkin pak supir membuka pintu untuk mempersilakan yang berbaik hati untuk turun di tempat itu dan bergantian dengan penumpang lainnya. Tapi nyatanya tidak. Tapi kalau pakai logika, supir itu agak bodoh juga nampaknya. Kalau saja para tujuan penumpang busway itu cuma shelter Mangga Dua, buat apa pula mereka ngantri sampai sejam dan berdesak-desakan? Dogol. Mungkin si supir penganut aliran eksistensialis yang menganggap orang-orang yang ingin diakui dengan cara iseng bin aneh tersebut masih mungkin hidup sampai sekarang, tepatnya di Jakarta dan sedang liburan di Ancol. Mungkin.
“Ini kami udah nunggu dari sejam yang lalu. Ini ada ibu-ibu bawa bayi, kasihan ini!” Itu ada suara seorang bapak yang gue ga liat mukanya karena gue menghadap ke sisi yang membelakangi shelter dan dengan posisi yang sangat tidak mungkin untuk melihat lebih dari 120 derajat dari sudut pandang normal. Seperti yang dia katakan, dia kesal karena harus menunggu kira-kira satu jam dan harus berbuah kekecewaan pahit tidak terangkut. Pasti dia lelah. Apalagi dia terpaksa harus marah-marah dengan situasi yang seperti ini.
“Oh iya. Bayinya kasihan tuh.” Kata seorang bapak dari dalam bis, posisinya kira-kira di sebelah kiri depan gue. “Tapi ibunya nggak.” Tandasnya lagi dengan intonasi yang cukup keras. “Bayinya biarin masuk aja!” Lanjutnya untuk menutup persoalan. Dan pintu ditutup, tanpa gue tau si bayi jadi masuk (bersama ibunya) atau nggak. Karena selain bis udah penuh sesak, gue juga nggak bisa nengok.
Akhirnya, memang betul, bis yang ini mengalami pecah ban depan kanan di Senen. Hingga harus berhenti 10 meter dari shelter. Karena saking keheranannya gue dan Ucok ketawa-ketawa dan lalu tos menggunakan tangan kanan, seolah kami penyebab semua masalah ini, padahal jelas-jelas kami korban. Si Ucok bersama puluhan penumpang lainnya dengan cepat memutuskan untuk turun di tempat itu lewat pintu darurat. Sedangkan gue dan sisa penumpang lain yang juga terlantar tenang-tenang saja tetap di dalam bis. Dan lalu, betapa beruntungnya gue dengan keputusan itu, karena 2 bis cadangan datang 10 menit setelahnya, dan gue naik ke bis kedua melanjutkan perjalanan transit ke Matraman, lanjut ke Manggarai.
Amin.
Quickview: nggak perlu, yang jelas ini bakalan panjang.
Sekedar kata pengantar yang sama sekali nggak ringkas.
Jam 6 sore gue memutuskan untuk ke studio (baca: lapak) Roni, temen residensi gue dari ISI. Seperti yang sering kita dengar dari para bhiksu, “Isi adalah kosong, kosong adalah isi”. Tapi Roni tidak beragama Buddha. Itu Trisno yang beragama Buddha, dan herannya dia juga dari ISI, tapi dia juga peserta residensi.
Sebelum cerita berlanjut, mungkin ada yang, walaupun ingin bertanya, tapi merasa hidupnya akan menjadi sia-sia jika harus sampai mengacungkan jari. Kenapa studio dalam tulisan ini harus dibaca lapak? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah karena memang lebih mirip lapak ketimbang studio.
Nah, tidak seperti yang kalian kira, gue ke studio Roni bukan untuk bicara dengan Roni. Gue ke sana justru karena tidak ada kepentingan apa-apa dengan Roni. Mungkin kalian yang membaca keheranan dengan tingkah laku gue, tapi gue pribadi udah nggak heran lagi dengan kalian yang begitu mudahnya keheranan.
Sampai di sana ternyata ada Ucok, itu temen dari ISI juga. Jadi kami bertiga di studio yang mirip lapak itu. Iqi a.k.a Chipow, Patriot a.k.a Mukmin a.k.a Majong, Luthfi a.k.a Bala, dan Walid sudah terlebih dahulu berpulang mendahului kami. Dua yang disebut pertama temen seangkatan gue dari ITB, dua sisanya dari IKJ. Jangan tanya gue mereka semua dari studio mana, tanya aja mereka kenapa milih studio itu. Karena dengan cara itu, kalian juga akan mendengarkan curhat mereka tentang dunia seni yang mereka geluti selama ini. Apa gunanya kalian bertanya mereka dari studio mana kalau kalian tidak tahu apa yang mereka kerjakan di studio? Atau jangan-jangan mereka memang tidak pernah bekerja di studio?
Nggak lebih dari semenit gue sampai sana, Ucok menerima telefon.
“Halo!” katanya. Tapi kata-kata selanjutnya gak gue pedulikan, karena buat apa mengurusi urusan orang lain? Mereka toh sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan masa depan mereka sendiri. Buktinya, toh mereka bisa jadi sarjana. Dan dari telefon itulah cerita berkembang, walaupun sama sekali nggak wangi.
“Eh!” Tegur Ucok, “Kau jadi balik sekarang?”
“Tar lagi. Napa? Lo mo cabut sekarang juga emangnya?”
“Iya. Aku harus ke Slipi. Males macetnya kalau kemalaman.” Ya, dari namanya kalian pasti tahu gimana cara dia ngomong kata males dan macet. Tapi kalau kalian ekspatriat, mungkin kalian tidak bisa mengimajinasikan apalagi menangkap apa yang saya maksud di sini.
Selanjutnya, gue akan melanjutkan kelanjutan cerita berlanjut ini sampai situ.
Pembicaraan berlanjut pada kesepakatan kami berangkat bareng setelah Ucok terlebih dahulu kencing di toilet umum yang disediakan gratis di sana. Dan walaupun dialog antara gue dan Ucok terjadi di studio Roni, tapi satu-satunya pembicaraan dengan Roni yang gue inget adalah saat gue mau cabut dan kami saling mengingatkan untuk berhati-hati. Entah apa maksudnya, mungkin sudah tradisi orang Jawa untuk mengatakan hal itu. Itu si Roni kalau tidak salah, berarti benar, dari Jepara.
Kami berjalan kaki hingga shelter bus Gondola dan menunggu bis gratisan yang melewati jalur arah barat. Bis pergi di saat kami masih sekitar 20 meter dari shelter. Tapi bis itu bukanlah satu-satunya di Ancol, seperti juga tidak cuma satu perempuan di dunia ini (Hey!). Maka kami tetap berjalan dengan langkah yakin. Jelas keyakinan kami tidak bertepuk sebelah tangan, karena setelah berdiri lama akhirnya bis yang lain datang. Kami masuk berebutan dan saling berdesakan. Tapi untung kami kebetulan pria lajang yang belum terikat perempuan manapun, jadi kalau bersenggolan tidak ada yang melarang (Hey!!). Kalaupun itu bukan muhrimnya tapi toh nggak ada yang protes. Karena bagaimana pun juga, sekedar bersenggolan di bis gratisan yang penuh sesak itu tidaklah bijaksana kalau sampai harus dibilang haram. Memang tak kenal maka tak sayang, tapi bukan berarti harus bermusuhan saat di naik bis berbarengan. Apalagi jika harus sampai pukul-pukulan. Sayangnya pertemanan pun sering pula dijadikan alasan untuk melambaikan tangan karena takut terdampar di tengah jalan (Hey!!!).
Tantangan selanjutnya, sekumpulan bau amburadul yang entah apa saja.
Asal tau saja, saat ini masih musim liburan anak sekolah. Herannya kenapa gue dan Ucok yang udah sarjana malah kena imbasnya. Buktinya, turun dari bis gratisan wara-wiri itu kami harus bersiap pula menghadapi antrian di bridge busway shelter. Waw! Itu istilah baru.
Gue kasih Rp 5.500,- ke mbak-mbak penjual karcis. Maksudnya biar dikasih kembalian Rp 2.000,- karena nanti gue naik bis Metro Mini nomer 62 dengan tarif segitu. Biar praktis. Uang kembalian dan karcis gue masukin kantong, dan karcis gue kasih ke petugas setelah gue kencing. Mungkin petugas itu tadinya pemarah, tapi kemudian dengan merobek-robek karcis dia menemukan ketenangan yang selama ini dia cari. Mungkin bagi anda yang pemarah, menjadi petugas penyobek karcis busway bisa menjadi pilihan terapi yang menarik.
Gue dan Ucok ngobrol sembari menunggu busway yang entah di mana supirnya. Heran, kenapa sebutannya busway padahal di badan bis jelas-jelas tulisannya Transjakarta? Tapi bukan itu yang kami obrolkan. Kami mengobrolkan bagaimana caranya berpameran di Galeri Soemardja. Agak geli juga sebenernya, direktur Galeri Soemardja namanya juga Ucok, dan gue biasa panggil dia Bang Ucok. Nah, kalau kata Bang dihilangkan, dalam konteks pembicaraan ini, yang akan merespon langsung adalah si Ucok temen gue yang dari ISI ini. Agak merepotkan emang. Tapi nggak apa-apa, karena ada busway lewat yang kontan disoraki “Huuu!!!” karena dia langsung cabut tanpa mengangkut satu penumpang pun. Hahaha, sialan.
Nah, nggak berapa lama setelah si pseudo-bus itu lewat, akhirnya datang bis gandeng yang mengangkut hampir setengah shelter. Dalam hati gue cuma bisa bilang “Sialan! Kenapa cuma bawa setengah shelter?” Akibatnya gue harus mengantri di samping cowok sok jangkung tapi gendut dengan bau keringatnya yang aduhai. Tapi biarin, pasang MP3 Homicide yang bising-bising juga sudah cukup membalaskan dendam gue. Nyahaha. Dan si cowok nampak kesal, mungkin karena dia keki tapi gengsi kalau harus sampai memamerkan kekuatannya di depan pacarnya. Tapi kalau dia mau ngajak bertengkar, ya nggak apa-apa. Bukankah bumbu pertengkaran yang baik akan mempererat ikatan pertemanan? Toh gue juga punya otak buat ngelawan ototnya dia, dan nggak mahir karate juga nggak berarti gue nggak bisa kung-fu. Nah, itu dia sudah kalah poin dari gue, karena itulah kami tidak sampai berkelahi. Walaupun dia sempat mendengus beberapa kali saat gue ganti track ke lagu Padi. Mungkin, karena yang di depannya itu bukan pacarnya, melainkan dia masih Menunggu Sebuah Jawaban (Hey!!!!). Tapi kalaupun benar gue nggak mau tau urusan orang lain, karena orang lain juga nggak pernah ngurusin gue. Toh gue juga memang dari dulu kurus, nggak seperti dia itu, gendut.
Setelah sengit bertengkar dalam pikiran kami masing-masing, dengan saling menghina dan melemparkan strategi, kami pun berbaikan. Kami saling meminta maaf dalam pikiran kami sendiri. Kebetulan bis datang, dan si Ucok dengan lekas mendorong gue masuk.
Dan hari belum berakhir. Masih ada kemungkinan nggak penting yang bisa saja akan terjadi. Sebut saja, seperti ban busway yang pecah mendadak di daerah Senen misalnya.
Bukan cuma gue kok yang nggak suka orang yang bertele-tele. Banyak juga orang yang ngaku begitu tapi omongannya muter-muter kayak keong (Hey!!!!!). Masalahnya, rumah keong itu mengikuti azas golden section (atau apalah itu namanya), makanya dia bisa oke. Mungkin orang yang bertele-tele tapi kalo mukanya kaya rumah keong bisa mendatangkan hoki juga. Nah, kalo gue bukan bertele-tele, tapi jelas-jelas ngelantur dan ngawur. Karena kalo nggak gitu cerita ini akan beres hanya dalam 1 paragraf. Coba liat, sejauh ini kalian sudah baca berapa? Karena kalau dibaca sampai sejauh ini, ceritanya memang nggak penting, tapi yang penting adalah memaknai sesuatu yang nggak penting hingga menjadi (seolah-olah) penting. Kalo boleh meminjam istilah yang pernah dilontarkan temen SMA gue dalam judul film pendeknya, Ignaz a.k.a Didz bersama Radian a.k.a Jawa, maka tulisan ini menjadi suatu Cela Cendekia yang menyenangkan. Setidaknya buat gue.
Ya, jadi ada satu dialog lucu yang terjadi di shelter Mangga Dua. Itu bis yang sama yang sedang gue naikin yang jadi saksi bisu dialog aneh ini. Bis yang sama yang harus berdesakan satu jam hingga akhirnya mau dinaiki. Dasar kuda!
Shelter itu penuh sesak dan sedari sejam yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan. Signifikan sih yang datang, tapi yang terangkut dikit. Dan bis berhenti di shelter itu, seperti biasa membuka pintu. Entah formalitas entah apa, pintu langsung ditutup kembali. Ya, jelas-jelas bisnya sudah penuh memang. Mungkin pak supir membuka pintu untuk mempersilakan yang berbaik hati untuk turun di tempat itu dan bergantian dengan penumpang lainnya. Tapi nyatanya tidak. Tapi kalau pakai logika, supir itu agak bodoh juga nampaknya. Kalau saja para tujuan penumpang busway itu cuma shelter Mangga Dua, buat apa pula mereka ngantri sampai sejam dan berdesak-desakan? Dogol. Mungkin si supir penganut aliran eksistensialis yang menganggap orang-orang yang ingin diakui dengan cara iseng bin aneh tersebut masih mungkin hidup sampai sekarang, tepatnya di Jakarta dan sedang liburan di Ancol. Mungkin.
“Ini kami udah nunggu dari sejam yang lalu. Ini ada ibu-ibu bawa bayi, kasihan ini!” Itu ada suara seorang bapak yang gue ga liat mukanya karena gue menghadap ke sisi yang membelakangi shelter dan dengan posisi yang sangat tidak mungkin untuk melihat lebih dari 120 derajat dari sudut pandang normal. Seperti yang dia katakan, dia kesal karena harus menunggu kira-kira satu jam dan harus berbuah kekecewaan pahit tidak terangkut. Pasti dia lelah. Apalagi dia terpaksa harus marah-marah dengan situasi yang seperti ini.
“Oh iya. Bayinya kasihan tuh.” Kata seorang bapak dari dalam bis, posisinya kira-kira di sebelah kiri depan gue. “Tapi ibunya nggak.” Tandasnya lagi dengan intonasi yang cukup keras. “Bayinya biarin masuk aja!” Lanjutnya untuk menutup persoalan. Dan pintu ditutup, tanpa gue tau si bayi jadi masuk (bersama ibunya) atau nggak. Karena selain bis udah penuh sesak, gue juga nggak bisa nengok.
Akhirnya, memang betul, bis yang ini mengalami pecah ban depan kanan di Senen. Hingga harus berhenti 10 meter dari shelter. Karena saking keheranannya gue dan Ucok ketawa-ketawa dan lalu tos menggunakan tangan kanan, seolah kami penyebab semua masalah ini, padahal jelas-jelas kami korban. Si Ucok bersama puluhan penumpang lainnya dengan cepat memutuskan untuk turun di tempat itu lewat pintu darurat. Sedangkan gue dan sisa penumpang lain yang juga terlantar tenang-tenang saja tetap di dalam bis. Dan lalu, betapa beruntungnya gue dengan keputusan itu, karena 2 bis cadangan datang 10 menit setelahnya, dan gue naik ke bis kedua melanjutkan perjalanan transit ke Matraman, lanjut ke Manggarai.
Amin.